“Wah, bacaannya buku berbahasa Inggris. Keren banget!”
“Wow, bacaanmu buku berbahasa Inggris, emang kamu ngerti, gitu?”
“Weleh, bacaannya buku berbahasa Inggris, dibaca beneran nggak, tuh? Cuma biar terlihat keren, ya?”
“Dih, bacanya buku berbahasa Inggris. Kenapa nggak baca terjemahannya saja? Nggak bangga sama bahasa sendiri.”
Kira-kira komentar-komentar seperti itu yang didengar
oleh Mbak Kim ketika dia ke mana-mana menenteng buku tebal The Name of The Rose versi bahasa Inggris terbitan Vintage. Dan tak
sebentar dia menenteng-nenteng buku itu, hampir sebulan! Rutinitas kantoran
pukul 7–16 bak kerangkeng bagi diri Mbak Kim, yang sebelumnya sungguh
mencintai pekerjaan sebagai pengangguran. Waktu untuk membaca jadi benar-benar
waktu yang dicuri. Makanya, ke mana-mana dia menenteng buku itu, setiap ada waktu
yang bisa dicuri, dia akan mencurinya seoptimal mungkin! Butuh waktu sekitar
satu bulan untuk menamatkan The Name of The
Rose, karena membaca buku itu berat—bilang
ke Dilan, tolong—tebal, 538 halaman; banyak sekali kata-kata bahasa Inggris
yang asing bagi Mbak Kim; Eco sering menuliskan deskripsi sesuatu dengan sangat
detail, dan itu malah bikin Mbak Kim makin pusing; bagian sejarah gereja
Katolik juga cukup membuatnya mumet. Namun, Mbak Kim tetap berusaha membacanya,
dan syukurlah, bisa menikmatinya, dan bisa sampai tamat. Membaca itu berat, lantas kenapa Mbak Kim tidak membaca yang versi terjemahan
Indonesia saja? Inilah hasil wawancara saya dengan blio.
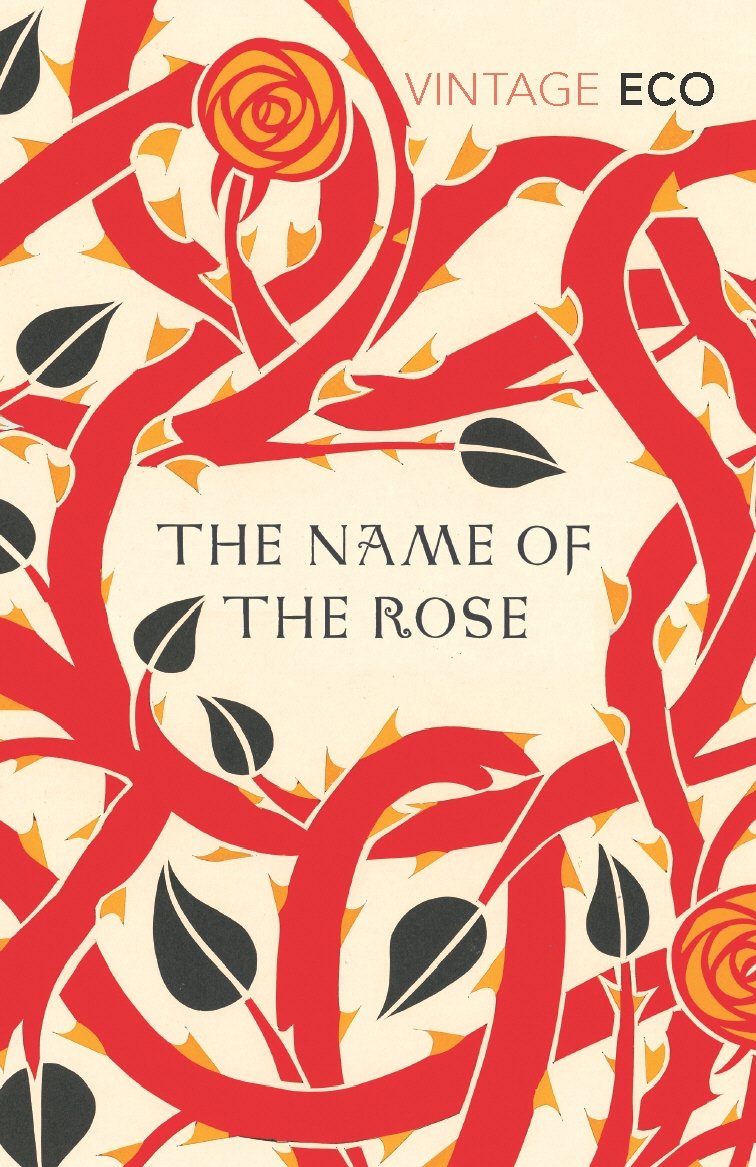 |
| Sumber gambar: Amazon |
***
Kenapa Mbak baca
The Name of The Rose versi bahasa Inggris? Padahal ada terjemahan Indonesianya,
kan?
Ada
pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Hmm, biar
terlihat keren, Mbak? Atau Mbak nggak bangga sama bahasa sendiri?
Tidak ada
hubungannya. Memilih baca buku berbahasa Inggris ketimbang versi terjemahan
Indonesianya, apakah itu lantas berarti minim kebanggaan terhadap bahasa
sendiri? Tidak, itu dua hal yang berbeda; dalam konteks pengalaman saya, tidak
ada hubungan kausal antara keduanya.
Atau, Mbak takut
kemampuan baca menurun karena baca versi bahasa Indonesia? Tahu nggak, sih,
Mbak, kelakuan seperti Mbak inilah yang bikin bangsa Indonesia jadi bermental
minderan!
Tidak ada
hubungannya lagi. “Minderan”? Minder sama siapa? Jangan-jangan, Anda sendiri
yang merasa begitu?! Bisakah kita
pindah ke hal substansial? Sukanya kok berputar-putar membahas aksesori.
Apakah Mbak tahu
kalau versi bahasa Inggrisnya itu pun terjemahan?
Pasti, dong.
Sebelum memutuskan untuk membeli (apalagi membaca)-nya, saya melakukan
“penyelidikan” dulu. Naskah aslinya ditulis Umberto Eco dalam bahasa Italia.
Lalu, kenapa
nggak milih yang terjemahan bahasa Indonesia? Toh, sama-sama “terjemahan”.
Tidak bisa
disamakan begitu saja, dong. Yang saya baca ini adalah terjemahan pertama
(langsung dari bahasa aslinya) oleh William Weaver. Nah, kalau yang terjemahan
Indonesia terbitan Bentang itu adalah terjemahan kedua, dari versi bahasa
Inggris terbitan Minerva tahun 1992; diterjemahkan oleh Nin Bakdi Soemanto.
Dalam proses penerjemahan, pasti ada yang “hilang” dan pasti terjadi “paralaks
makna”. Itu tak bisa dihindari. Yang “hilang” ini akan semakin banyak, dan
“paralaks makna” akan semakin besar, jika karya tersebut diterjemahkan bukan
dari bahasa aslinya. Makanya, prinsip membaca saya, salah satunya adalah sebisa
mungkin membaca suatu karya dalam bahasa aslinya. Namun, karena saya nggak bisa
bahasa Italia, maka saya pilih terjemahan bahasa Inggris The Name of The Rose.
Tadi Mbak bilang
bahwa baca The Name of the Rose
ini “berat”. Namun, kenapa Mbak tetap
membacanya?
Karena untuk
menikmati keindahan alam dari puncak gunung, kita harus bersusah-payah jalan
kaki menanjak selama berjam-jam dulu, Mbak. Dengan baca buku itu, saya bisa
belajar bahasa Inggris lebih banyak, apalagi banyak kosakata yang baru bagi
saya. Biar kemampuan berbahasa Inggris saya tidak lekas luntur (maklum, jarang
digunakan secara lisan di sini). Oleh karena ini terjemahan pertama, maka
pemahaman saya akan isinya mungkin sekali lebih akurat ketimbang jika saya baca
terjemahan kedua, ketiga,...
Selain yang Mbak
paparkan sebelumnya, apakah ada pertimbangan lain kenapa memilih versi
terjemahan bahasa Inggris?
Ada. Sederhana
saja alasannya: harganya lebih murah ketimbang versi terjemahan bahasa
Indonesia. Saya dapat harga 65 ribu di Big Bad Wolf (ups, harga aslinya 7,99 EUR atau sekitar 135 ribu rupiah), sedangkan yang
terbitan Bentang Pustaka edisi sampul baru terbitan tahun 2017 dibanderol 99
ribu. Dan, Anda mungkin juga tahu kalau buku-buku terbitan Indonesia sekarang
trennya cenderung makin mahal.
Lalu, apakah ini
berarti Mbak tidak mau membaca buku terjemahan Indonesia?
Duh, lagi-lagi
Anda memaksakan hubungan kausal... Tidak begitu juga, dong. Saya tetap suka
membaca terjemahan Indonesia. Ada beberapa terjemahan Indonesia yang saya
sukai, misalnya seri Harry Potter terjemahan
Listiana Srisanti. Saya juga memilih mengoleksi versi bahasa Indonesianya,
karena sampul barunya cantik sekali (padahal harga buku ketiga sampai
ketujuhnya lebih mahal ketimbang versi asli
berbahasa Inggris terbitan Bloomsbury edisi paperback
terbitan tahun 2014).
 |
| Lihatlah harga yang mencekik ini, Saudara-saudara! Dan Mbak Kim masih harus melengkapi koleksinya dengan buku ketujuh, yang harganya "berkepala" tiga! Sumber gambar: Gramedia |
 |
| Ini versi Bloomsbury yang Mbak Kim maksudkan. Sumber gambar: Pinterest |
Saya juga suka A Game of Thrones terjemahan Barokah Ruziati, juga cerpen-cerpen terjemahan
Maggie Tiojakin. Untuk beberapa buku nonfiksi, saya lebih nyaman membaca versi
terjemahan Indonesianya, seperti Sejarah
Tuhan terjemahan Zaimul Am. Beberapa novel terbitan Spring juga bagus terjemahannya, seperti The Girl on Paper, yang diterjemahkan
oleh Yudith Listiandri.
Namun, saya
sering menjumpai terjemahan Indonesia yang ambyar.
Itulah alasan mengapa saya berhati-hati dalam memilih buku terjemahan
Indonesia. Misalnya, yang beberapa bulan lalu saya baca (dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti membacanya sebelum tamat karena saya tak kuat--terjemahannya terlalu!), Second Sex: Kehidupan Perempuan terbitan Narasi, terjemahan Nuraini Juliastuti. Banyak bagian yang
bikin saya gagal paham, antara lain karena pemilihan kata tidak sesuai konteks.
Diperparah dengan ejaannya tidak disempurnakan, seperti banyaknya tanda titik
hilang dan malah menyelip ke tempat yang tidak seharusnya.
 |
| Sumber gambar: Goodreads |
Jadi, terjemahan
Indonesia yang bagus itu yang seperti apa, Mbak?
Ya, yang seperti
beberapa judul buku yang saya sebutkan tadi. Terjemahan yang kalau dibaca rasanya
tidak seperti terjemahan; seolah-olah karya tersebut memang aslinya ditulis
dalam bahasa Indonesia.
Antara buku
berbahasa Inggris dan terjemahan Indonesia, Mbak pilih yang mana?
Lho, kok Anda
malah mundur ke titik awal pembahasan? Kita sudah sampai sini, lho. Sudah saya
jabarkan mengapa untuk kasus tertentu saya memilih versi bahasa Inggris, dan
kenapa untuk kasus lain saya pilih versi terjemahan Indonesia. Tidak bisa
“pilih yang mana antara keduanya” karena untuk tiap kasus saya punya
pertimbangan-pertimbangan tertentu yang spesifik. Tak mustahil juga untuk satu
judul karya saya membaca versi bahasa Inggris juga versi Indonesianya.
Bagaimana kalau
wawancara ini saya beri judul “Buku Berbahasa Inggris versus Terjemahan
Indonesia: Sudut Pandang Seorang Pembaca”?
Wah, jangan
seperti itu. Mengapa keduanya harus diversuskan?
***
Demikianlah, akhirnya kata “versus” saya ganti menjadi
“dan”. Semoga terjemahan-terjemahan Indonesia meningkat terus kualitasnya
sehingga memuaskan para pembaca yang pemilih dan kritis seperti Mbak Kim
tersebut. Dan semoga tak ada lagi pertanyaan “pilih mana antara versi bahasa
Inggris atau versi terjemahan Indonesia” tanpa batasan yang spesifik dan jelas.
Kalau tidak, pembahasan itu tak akan ke mana-mana, mungkin hanya akan berakhir
jadi debat penuh emosi (kecuali kalau memang sengaja mau memancing emosi dan
sensasi). Biar viral, katanya. Ah!
Ah, terakhir, mungkin Anda semua perlu tahu bahwa
wawancara tersebut adalah wawancara dengan diri saya sendiri yang berlangsung di
dalam pikiran. Hihihi.[]






0 komentar:
Post a Comment
Your comment is so valuable for this blog ^^